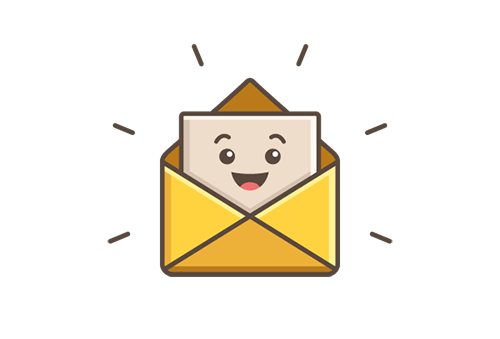Udah pernah dengar istilah performative male, kan? Iya, yang biasanya dipake buat jelasin cowok-cowok yang sok-sokan suka sesuatu atau ngelakuin hal tertentu cuma biar keliatan keren atau menarik di mata cewek.
Tapi ternyata, versi ceweknya juga ada, lho. Namanya performative femininity atau kadang disebut performative female. Terus, bedanya apa? Yuk kita kupas tuntas.
Kalau performative male itu soal cowok yang “pura-pura”, performative femininity itu soal cewek yang ngelakuin hal-hal feminin secara sadar, tapi bukan karena emang dari hati nurani mereka, melainkan buat memenuhi ekspektasi sosial atau mencari perhatian orang lain.
Contohnya nih:
- Cewek yang selalu senyum manis padahal lagi bete banget.
- Selalu ngomong lembut biar dibilang “feminim”.
- Pakai baju tertentu cuma biar dianggap stylish dan cocok sama image cewek ideal.
Jadi intinya, feminitasnya itu kayak dipentaskan, bukan asli dari diri mereka sendiri.
Dari Filsafat Sampai Gender: Cerita Performativitas
Konsep performatif sebenernya udah lama dibahas. Filsuf Inggris J.L. Austin di tahun 1950-an ngomong kalo ada ucapan yang nggak cuma buat ngasih info, tapi sekaligus menciptakan aksi.
Misalnya pas nikah: bilang “aku janji setia” itu nggak cuma kata-kata, tapi langsung jadi aksi yang mengikat seumur hidup.
Nah, dari sini muncul ide performatif di banyak bidang, termasuk soal gender.
Judith Butler dan Performa Gender
Judith Butler, tokoh feminis dan filsuf, di bukunya Gender Trouble (1988) bilang kalau gender itu bukan bawaan lahir.
Identitas gender terbentuk lewat perilaku, gaya, dan kebiasaan yang terus diulang sesuai standar sosial. Jadi, gender itu performatif—seolah alami, padahal sebenernya dibentuk oleh lingkungan.
Makanya, performative femininity itu muncul karena tekanan sosial. Cewek ngerasa wajib selalu tampil lembut, peduli, dan cantik biar diterima. Padahal itu bukan murni dari diri mereka.
Nggak Jauh Beda Sama Performative Male
Fenomena ini nggak cuma terjadi sama cewek, cowok juga bisa. Ingat tren soft boy yang lagi hits? Banyak cowok tiba-tiba baca buku feminis, minum matcha latte, atau koleksi boneka cuma biar keliatan “penuh perasaan” di mata cewek.
Jadi, baik cowok maupun cewek bisa sama-sama performatif kalo tujuannya lebih ke pencitraan ketimbang ekspresi diri asli.
Tekanan Sosial: Efek Samping Performative Femininity
Nggak semua ekspresi feminin itu performatif, kok. Ada cewek yang emang seneng dandan, pakai rok, atau ngomong lembut karena itu bagian dari diri mereka. Tapi kalo muncul karena tekanan sosial, bisa bikin masalah:
- Turunnya kepercayaan diri karena standar sosial sering nggak realistis.
- Di dunia kerja, cewek tegas sering dicap agresif, sementara cowok tegas dianggap pemimpin.
Media juga ikut andil, lho. TV, iklan, media sosial sering nunjukin “cewek ideal”: flawless, langsing, dan lembut. Jadinya banyak cewek ngerasa harus ikut standar itu, meski nggak nyaman.
Efeknya? Bisa muncul kecemasan, rasa nggak cukup, atau depresi.
Kalau dilakukan dengan sadar, performative femininity bisa jadi cara ekspresi diri sekaligus strategi pemberdayaan.
Cewek bisa pilih berdandan atau tampil feminin bukan karena paksaan, tapi karena itu cara mereka nunjukin identitas sendiri.
Intinya: yang penting itu beda-bedain ekspresi feminin asli vs. yang dipaksain sama tekanan sosial. Dengan begitu, cewek bisa lebih bebas nunjukin siapa dirinya tanpa harus selalu main di panggung orang lain.